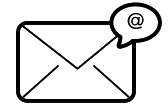Maulid Nabi dan Jalan Pulang Bangsa
Abdurrahman Wahid
Pengurus Depertemen SDI DPP HEBITREN, Ketua P4NJ Jabodetabek-banten dan CEO Kita Santri
Kemerdekaan baru saja kita rayakan dengan gegap gempita, tetapi itu juga menutup dirinya dengan kelabu: rakyat dipentung, bahkan seorang pengemudi ojek online bernama Affan meregang nyawa. Di tengah kabut krisis ini, Maulid Nabi hadir sebagai cahaya, mengingatkan kita pada teladan Rasulullah yang menyatukan, bukan memecah; yang menyejukkan, bukan menindas.
Beritabaru.co -Indonesia baru saja merayakan kemerdekaan ke-80. Bendera merah putih berkibar gagah di gang-gang sempit, di jalan-jalan kota, bahkan di depan rumah kontrakan sederhana. Seolah semua ingin berkata: kita sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang tampak di mata sering kali tak sejalan dengan kenyataan di hati rakyat. Harga beras kian melambung, utang negara menggunung, pajak tumbuh bagai jamur di musim hujan. Rakyat kecil tak lagi punya ruang untuk bernapas lega.
Sementara itu, di gedung-gedung berpendingin, para elit menari di atas panggung kekuasaan. Mereka menambah tunjangan, menumpuk jabatan, dan tersenyum puas seakan negeri ini warisan keluarga. Kita, rakyat yang mereka wakili, hanya bisa mengelus dada. Kita berutang di warung, sementara mereka kekenyangan di meja makan negara. Ada luka yang makin dalam: kemerdekaan ternyata masih lebih terasa sebagai janji, bukan kenyataan.
Ketika rakyat mulai bersuara, menggunakan hak konstitusional yang katanya dijamin undang-undang, yang datang bukan telinga untuk mendengar, melainkan pentungan, gas air mata, dan intimidasi. Tragedi pun lahir: Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meregang nyawa. Ia bukan orator, bukan provokator, bukan tokoh besar yang biasa disorot kamera. Ia hanya rakyat kecil, kebetulan berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Tetapi darahnya menetes, menjadi saksi bahwa harga sebuah nyawa di negeri ini bisa begitu murah di hadapan demokrasi yang kian rapuh.
Kisah Affan adalah bara kecil yang menyentuh bensin. Rakyat turun ke jalan di berbagai daerah, membawa poster, suara, dan air mata. Mereka menuntut keadilan, bukan kemewahan. Tetapi, apakah jeritan itu didengar? Para penguasa tampaknya lebih peka pada dering notifikasi rekening bank daripada pekik luka rakyat.
Rakyat memang terbiasa menanggung derita dengan tabah, tetapi setiap kesabaran ada batasnya. Kesedihan yang menumpuk bisa berubah menjadi amarah, dan amarah yang dibiarkan bisa menyapu apa saja yang menghalangi. Bukankah tugas pemimpin adalah merawat, mendengar, dan menanggung bersama — bukan sekadar mengelola kursi kekuasaan?
Di tengah kegaduhan bangsa, kita kerap lupa bahwa sejarah pernah melahirkan manusia sederhana, tanpa pesta atau seremonial, namun dari kesahajaannya memancar cahaya yang tak pernah padam — Nabi Muhammad. Beliau bukan hanya hadir untuk menghibur hati yang gundah, tetapi juga mengubah arah sejarah, menghadirkan peradaban baru yang dibangun di atas keadilan, persamaan, dan akhlak mulia. Dari tangannya lahirlah masyarakat madani, sebuah tatanan hidup yang menempatkan manusia sebagai sesama, bukan sebagai alat atau angka, dan menjadikan kemerdekaan sejati bertumpu pada martabat serta kasih.
Sayangnya, Maulid sering kita rayakan hanya sebagai pesta seremonial: rebana ditabuh, nasi tumpeng dipotong, ceramah formal dibacakan. Padahal, sejatinya Maulid adalah ruang refleksi: menyalakan kembali obor akhlak di tengah kabut zaman. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan gelar profesor, tidak kekurangan politisi pandai pidato. Yang hilang justru kehalusan budi, kelembutan hati, dan kasih pada sesama.
Mari kita tengok sebentar akhlak Sang Nabi. Ketika suku-suku Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, beliau tidak memihak. Tidak pula menyulut konflik agar kursi empuknya makin kokoh. Beliau bentangkan sehelai kain, mengajak semua ikut mengangkat batu suci itu bersama-sama. Solusi jenius, sederhana, tetapi menyatukan.
Atau Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menyatukan Muslim, Yahudi, Nasrani, dan berbagai suku dalam satu ikatan persaudaraan. Bandingkan dengan negeri kita: membuat undang-undang sering kali lebih mirip dagang sapi daripada piagam persaudaraan.
Bahkan ketika beliau dihina, dilempari batu, dan diludahi, balasan beliau bukan amarah, melainkan kasih. Seorang Yahudi yang meludahinya setiap hari justru beliau jenguk saat sakit. Seorang pengemis buta yang menghinanya justru beliau beri makan dengan tangannya sendiri. Bandingkan dengan kita hari ini: seorang netizen salah komentar sedikit, langsung diseret dengan pasal ITE.
Akhlak Nabi adalah jalan pulang bangsa ini. Politik tanpa empati, kekuasaan tanpa cinta, hukum tanpa welas asih — itulah penyakit kita sekarang. Kita terjebak dalam demokrasi prosedural yang penuh janji manis, tapi kosong dari nurani. Kita sibuk menebang pohon demi kursi, tapi lupa menanam kembali akar moral yang membuat bangsa ini tegak.
Maulid adalah momentum muhasabah, taubat kebangsaan. Sudah cukup, tidak ada demokrasi seharga nyawa. Demokrasi seharusnya membuat rakyat hidup lebih layak, bukan malah menambah beban. Demokrasi seharusnya menyatukan, bukan menggebuk. Demokrasi seharusnya menghadirkan senyum anak-anak di sekolah, bukan tangisan ibu-ibu di dapur karena harga minyak goreng naik lagi.
Barangkali bangsa ini perlu belajar lagi dari kelahiran Nabi. Ia lahir yatim, miskin, tanpa fasilitas negara, tapi membawa cahaya bagi seluruh peradaban. Sementara para pejabat kita lahir dengan sendok emas, bergelimang fasilitas, tapi sering kali hanya membawa gelap bagi rakyat. Ironi ini semestinya jadi cambuk, bukan malah jadi bahan tertawaan di ruang rapat.
Kalau Maulid hanya jadi pesta seremonial tanpa refleksi, kita akan terus jalan di tempat: semakin jauh dari Nabi, semakin dekat dengan keserakahan. Tetapi jika Maulid kita rayakan sebagai momentum untuk kembali pada akhlak, pada kasih, pada keadilan, mungkin bangsa ini bisa menemukan jalan pulangnya.
Dan jalan pulang itu sederhana: berhenti berjoget di atas penderitaan rakyat, berhenti menumpuk jabatan seakan dunia ini abadi, berhenti membuat undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir. Mulailah dengan empati, dengan kesadaran bahwa kekuasaan itu amanah, bukan warisan.
Sebab sejatinya, bangsa ini tidak butuh pejabat yang pandai beretorika, melainkan pemimpin yang berani turun menyentuh lumpur rakyat. Tidak butuh penguasa yang pandai bikin jargon, melainkan pemimpin yang tahu cara membagi roti, walau hanya sepotong. Tidak butuh drama politik yang panjang, melainkan kebijaksanaan sederhana ala Nabi: membentangkan kain, mengajak semua memikul bersama.
Itulah Maulid. Itulah jalan pulang bangsa.
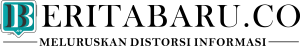
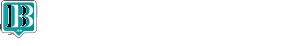
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co