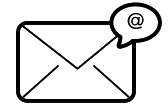Gus Muhaimin: Santri di Panggung Politik
Abdurrahman Wahid
(Pengurus SDI DPP HEBITREN & Ketua P4NJ Jabodetabek-Banten)
Beritabaru.co – Politik, sejak dulu, memang tak pernah jauh dari panggung. Di situ ada aktor, ada naskah, ada sorakan penonton, ada pula jatuh-bangun yang sering lebih dramatis dari pada drama Korea. Bila kita menyebut nama Muhaimin Iskandar, sebenarnya kita sedang menunjuk salah satu aktor kawakan dalam panggung itu. Seorang yang tahu kapan mesti tersenyum, kapan melipat tangan, kapan menunduk, dan kapan melompat dengan langkah tak terduga.
Tokoh asal Jombang ini lahir dari keluarga besar pesantren. Ia cucu KH. Bisri Syansuri, tokoh besar NU yang namanya harum di kitab sejarah. Nasab seperti ini tak bisa dibeli dengan mahar politik, apalagi dengan uang sogokan. Ia seperti tiket emas untuk memasuki gelanggang politik Indonesia yang penuh intrik. Bagi sebagian orang, nasab itu adalah jubah yang membuat langkah tegap meski di tengah hujan kritik.
Bayangkan seorang pemuda yang lebih akrab dengan kitab kuning dan aroma tembakau santri, pada usia 33 tahun sudah dipercaya duduk di kursi DPR RI. Dari sana, kiprahnya berlanjut hingga dipercaya memimpin PKB sebagai ketua umum. Perjalanan politik itu kemudian mengantarkannya menjadi menteri, lalu melangkah lagi ke kursi Wakil Ketua DPR. Bila politik dianalogikan sebagai sebuah panggung besar, maka sosok ini bisa disebut pesulap ulung: ia mampu menghadirkan kejutan demi kejutan, bahkan ketika banyak penonton merasa sudah memahami trik lamanya.
Keahliannya bukanlah membuat pidato yang membakar, bukan pula menyusun teori politik sekelas Montesquieu. Ia jago membaca tanda-tanda zaman. Di era ketika politik identitas mulai memudar digantikan logika pasar dan dunia digital, ia tahu betul bahwa sarung dan peci saja tidak cukup. Partai pun dijual dengan bumbu baru: milenial, generasi Z, media sosial. “Dulu kita jualan sarung dan peci,” begitu ia bisa berkelakar, “sekarang kita jualan anak muda, laptop, dan kopi susu kekinian.” Dan jangan salah, dagangan ini laris manis.
Lihat saja hasilnya. Pemilu 2009 PKB hanya mendapat 5 jutaan suara. Tapi begitu menggandeng nama besar Mahfud MD dan suara emas Rhoma Irama di Pemilu 2014, perolehan partai melesat jadi lebih dari 11 juta. Strategi branding, kata para konsultan politik, tapi sebenarnya itu hanya siasat santri: tahu kapan harus ngaji, kapan harus dagang, kapan harus pura-pura tidur di serambi pesantren.
Namun, panggung politik selalu menuntut babak baru. Di Pemilu 2019, PKB kembali naik dengan 13 juta suara lebih, bahkan belakangan tembus 16 juta. Itu artinya, strategi sang ketua partai makin diterima. Orang-orang desa yang terbiasa mendengar ceramah kiai, kini bisa menyapa partai berbasis tradisi ini melalui aplikasi ponsel. Politik pun akhirnya bisa masuk ke layar sentuh.
Tentu saja perjalanan ini tidak semulus jalan tol yang diresmikan presiden. Ada lubang-lubang dalam kariernya. Ia pernah dianggap terlalu lihai, bahkan licin. Kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa tiba-tiba dipeluk mesra di depan kamera. Politik memang begitu. Hari ini berkoalisi, besok berpisah dengan senyum. Seseorang bisa bersumpah setia di pagi hari, lalu sore harinya pindah gerbong. Seperti kata orang Jawa, politik itu mambu kembang sore: harum sebentar, lalu layu ketika senja datang.
Kisah paling menggelitik tentu saat ia tiba-tiba diumumkan menjadi cawapres Anies Baswedan. Padahal, baru beberapa hari sebelumnya terlihat hangat bersama barisan Prabowo. Penonton politik tentu ternganga, tapi sang ketua partai tampak biasa saja. Baginya, berpindah panggung itu seperti santri pindah langgar: yang penting niatnya masih sama, untuk belajar dan memperjuangkan.
Namun drama politik tak berhenti di situ. Tiba-tiba, setelah episode pilpres itu berlalu, ia justru masuk dalam kabinet merah putih sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat di bawah komando Presiden Prabowo. Langkah ini bisa dipahami lewat kaidah ushul fiqh: mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu—apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, maka tidak ditinggalkan seluruhnya. Artinya, meski kursi yang lebih tinggi belum berhasil dicapai, kesempatan yang terbuka tetap harus dimanfaatkan. Menjadi bagian dari kabinet bukan sekadar soal jabatan, melainkan ikhtiar untuk menjaga eksistensi partai, memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, dan memastikan suara pesantren hadir dalam arah kebijakan negara.
Di balik semua kelicahannya, tetap ada yang khas darinya: ia tumbuh dari kultur pesantren. Itu artinya, ia terbiasa dengan tradisi Islam Nusantara—Islam yang ramah, yang tidak kaku, yang bisa bergurau sekaligus merenung. Di satu sisi ia bisa serius bicara soal demokrasi, di sisi lain ia bisa bercanda tentang sarung yang melorot. Inilah daya tarik politik ala pesantren: jenaka tapi tajam, sederhana tapi penuh perhitungan.
Kita mungkin bertanya-tanya: apakah hatinya masih lembut seperti hati santri yang mengaji kitab kuning? Atau sudah berubah sekeras baja akibat badai politik yang terus-menerus menghantam? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Ia tahu kapan harus melunak, kapan harus mengeras. Ia tahu kapan harus menunduk di depan kiai, kapan harus berdiri tegak di depan presiden. Itulah seni bertahan hidup di rimba kekuasaan.
Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari lakon panjang ini? Bahwa politik, betapapun kotor dan melelahkan, tetap membutuhkan sentuhan kebudayaan. PKB di tangannya bukan sekadar partai politik; ia adalah panggung di mana tradisi dan modernitas bisa menari bersama. Ia mengingatkan kita bahwa Indonesia, dengan segala kebhinnekaannya, tetap butuh jembatan. Dan barangkali, dalam sosok ini, jembatan itu sedang diuji: kuatkah ia menahan arus deras zaman?
Kritik tentu tetap perlu. Jangan sampai kelincahan berubah jadi kelicinan, jangan sampai strategi berubah jadi oportunisme. Politik bukan sekadar seni berpindah koalisi, tapi juga seni menjaga integritas. Jika sarung dan peci dulu dijual sebagai simbol kesalehan, maka kini simbol-simbol digital jangan sampai hanya menjadi kosmetik. Kita ingin agar politik tak kehilangan ruh: ruh untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar memenangkan kursi.
Tapi kita juga tahu, sejarah politik Indonesia selalu penuh paradoks. Kadang yang kita anggap oportunis justru paling bertahan lama. Kadang yang dianggap idealis justru cepat tersingkir. Dalam dunia seperti ini, mungkin kita butuh orang yang bisa menari di antara hujan, yang bisa tertawa di tengah badai, yang bisa membuat politik terasa seperti guyonan warung kopi—serius tapi tetap ringan.
Maka, ketika pada bulan September ini Gus Muhaimin merayakan hari lahirnya, kado terbaik barangkali bukanlah pesta atau gemerlap ucapan, melainkan doa yang tulus. Doa agar ia senantiasa ingat, sebesar apa pun kursi kekuasaan yang diduduki, politik hanyalah panggung sementara. Yang abadi adalah pengabdian, yang kekal adalah ketulusan. Sarung boleh lusuh, kursi bisa bergeser, tetapi nama baik akan tetap tercatat dalam sejarah—jauh lebih lama daripada tepuk tangan penonton politik yang sering lekas reda.
Dan bila suatu hari kelak ia duduk di kursi yang lebih tinggi lagi, semoga tak lupa pada suara santri kecil di pesantren, suara rakyat kecil di desa, suara petani yang menggantungkan hidup pada tanahnya. Karena tanpa mereka, panggung politik hanyalah panggung kosong, dan aktornya hanyalah badut yang menertawakan dirinya sendiri.
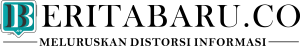
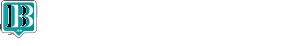
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co