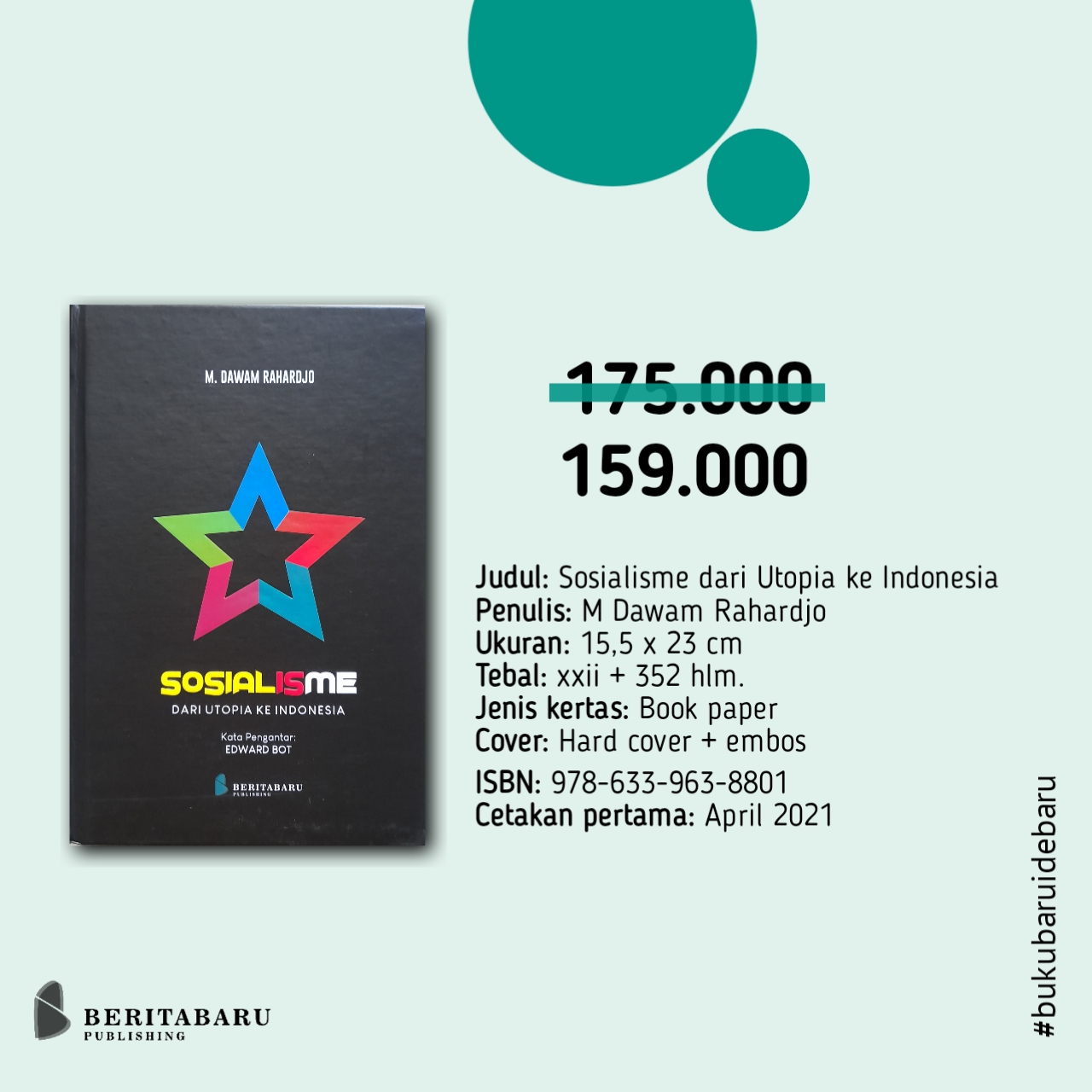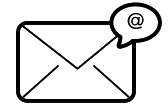Linearitas Guru dan Birokrasi Pendidikan | Opini: Musyarrafah S.
Mengapa sekolah-sekolah di Indonesia begitu tertutup terhadap keterlibatan para profesional sesuai bidang yang dibutuhkan?
Pertanyaan ini relevan di tengah kompleksitas pendidikan abad ke-21, ketika ilmu pengetahuan dan keterampilan berkembang dengan sangat cepat. Alih-alih membuka ruang bagi tenaga pendidik yang kompeten, sekolah justru memilih jalan sebaliknya: memaksa guru mengajar di luar bidang keilmuannya. Fenomena ini sudah demikian lazim hingga dianggap wajar, meskipun sesungguhnya merupakan bentuk delegitimasi terhadap profesionalisme guru sekaligus pelemahan mutu pendidikan.
Salah satu akar masalah dapat ditelusuri pada cara birokrasi pendidikan memandang posisi guru. Dalam logika birokrasi Weberian, guru lebih diperlakukan sebagai aparatur yang dapat digerakkan sesuai kebutuhan administrasi daripada sebagai subjek pengetahuan dengan otoritas akademik. Maka, ketika terjadi kekosongan formasi guru pada mata pelajaran tertentu, solusi birokratis yang diambil bukanlah menghadirkan tenaga ahli, melainkan mendistribusikan beban itu kepada guru yang tersedia. Rasionalitas yang dipakai bukan rasionalitas substantif yang menekankan kualitas pembelajaran, melainkan rasionalitas administratif yang mengutamakan efisiensi semu, yaitu bagaimana jam terisi dan struktur berjalan.
Konsekuensi dari pola pikir ini adalah terjebaknya pendidikan pada ilusi efisiensi. Teori human capital dengan tegas menekankan bahwa investasi pada tenaga pendidik yang tepat akan menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang. Namun di Indonesia, efisiensi dipahami secara reduktif hanya sebagai penghematan biaya jangka pendek. Tidak merekrut tenaga ahli dianggap hemat, padahal kerugian riil jauh lebih besar: siswa menerima pelajaran bukan dengan ahlinya, keterampilan abad ke-21 gagal dicapai, dan pendidikan berhenti pada level administratif belaka.
Ironi semakin kentara jika menengok praktik rekrutmen guru ASN maupun non-ASN. Secara normatif, seleksi ASN dirancang untuk menjamin mutu pendidikan dan memastikan adanya linearitas antara bidang studi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Namun dalam praktik, linearitas lebih sering dimaknai sebatas konstruksi administratif daripada kesesuaian epistemologis dengan disiplin ilmu yang sebenarnya. Sebagai contoh, seorang lulusan matematika dapat dianggap linear untuk mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya karena argumentasi administratif bahwa keduanya sama-sama berkaitan dengan “logika” atau “hitung-hitungan”. Demikian pula, lulusan ekonomi bisa dipandang linear dengan prakarya, atau lulusan biologi disetarakan dengan pendidikan jasmani karena sama-sama bersentuhan dengan aspek tubuh. Pemaknaan semacam ini jelas mengabaikan substansi keilmuan dan kompetensi pedagogis yang seharusnya melekat pada profesi guru.
Persoalan linearitas semakin rumit dengan hadirnya jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG). Secara formal, PPG memang dimaksudkan untuk memastikan guru memiliki sertifikat pendidik dan kompetensi profesional. Namun pada praktiknya, PPG juga membuka jalan bagi lulusan non-pendidikan untuk bertransformasi menjadi guru hanya dengan mengikuti program tersebut. Seorang sarjana murni ilmu murni atau bahkan lulusan disiplin non-keguruan dapat mengajar jika berhasil menyelesaikan PPG. Hal ini menimbulkan paradoks baru: di satu sisi pemerintah menekankan pentingnya linearitas dan kompetensi; di sisi lain, pintu masuk profesi guru diperluas dengan basis kualifikasi administratif (sertifikat PPG), bukan kualifikasi substantif yang teruji dalam pengalaman pedagogis.
Praktik pengabaian linearitas sejatinya melanggar amanat Undang-Undang Guru dan Dosen yang menekankan kompetensi profesional sebagai salah satu pilar utama. Siswa pada akhirnya menjadi korban langsung. Bagaimana mungkin peserta didik memperoleh keterampilan digital dari guru yang latar belakang akademiknya bukan teknologi? Mata pelajaran TIK yang seharusnya membuka horizon digital generasi muda akhirnya tereduksi menjadi sekadar pelatihan mengetik atau membuat slide presentasi. Aspek-aspek strategis seperti coding literacy, keamanan siber, atau etika digital tidak tersentuh karena gurunya sendiri tidak memiliki basis keilmuan memadai. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya praktik pendidikan kita dari teori konstruktivisme Piaget maupun Vygotsky yang menekankan pengalaman belajar otentik sebagai basis pembentukan pengetahuan.
Paradoks pendidikan Indonesia semakin jelas: guru diagungkan sebagai profesi mulia dengan standar kompetensi tinggi, tetapi profesionalisme itu justru ditanggalkan sejak awal rekrutmen dengan logika linearitas semu. Guru diperlakukan semata-mata sebagai instrumen birokrasi yang dapat digerakkan sesuai kebutuhan jam, bukan sebagai subjek berpengetahuan yang otonom. Paulo Freire sudah mengingatkan bahwa pendidikan yang menempatkan guru hanya sebagai alat adalah pendidikan yang menindas. Dalam konteks kita, guru tidak hanya diperlakukan sebagai alat, tetapi juga dipaksa memainkan partitur yang bahkan tidak pernah mereka pelajari.
Pertanyaan yang tersisa adalah apakah sistem pendidikan Indonesia sungguh berupaya membangun generasi masa depan atau sekadar memelihara kelangsungan birokrasi. Di tengah retorika pendidikan bermutu, ku (rikulum merdeka, dan wacana pembelajaran abad ke-21, realitas di lapangan justru menampilkan kontras: siswa belajar dari guru yang tidak sepenuhnya menguasai bidangnya, guru susah payah bertahan di luar kompetensinya, sementara birokrasi bersembunyi di balik bahasa “linearitas”.
Misteri mengapa sekolah enggan melibatkan profesional sesungguhnya tidak lagi misteri, melainkan cermin dari kemalasan sistemik untuk berubah.

Musyarrafah S. adalah kontributor opini Beritabaru, peneliti Oase Institute, dan pengkaji pendidikan dan sastra
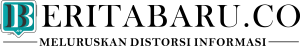

 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co