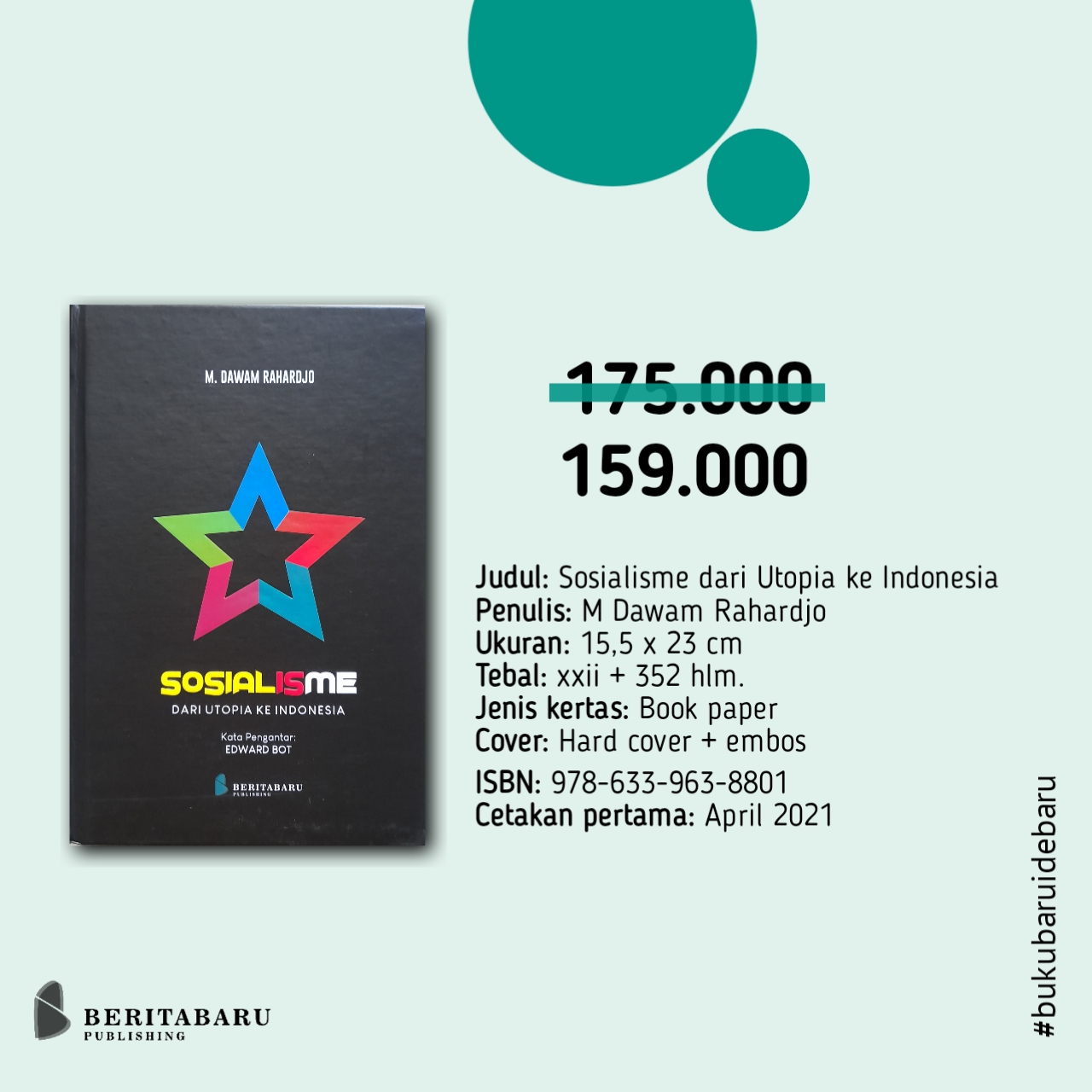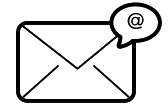Bantuan dalam Pendidikan: Narasi Kewajiban yang Disulap Jadi Derma I Opini: Musyarrafah S
Dengan suara pelan tapi penuh rasa syukur, ia bilang bahwa anaknya yang masih duduk di SD dapat bantuan dari pemerintah. Uangnya Rp 400 ribu. “Buat beli seragam sama sepatu,” katanya. Saya ikut senang, tentu saja. Tapi entah kenapa, setelah ia pergi, saya malah termenung. Kenapa ya, bantuan seperti ini selalu terdengar seperti kebaikan hati yang luar biasa, padahal… bukankah itu memang tugas negara?
Di negeri ini, kata “bantuan” tampaknya telah naik kasta. Ia bukan lagi sekadar istilah teknokratis, tetapi telah menjelma menjadi mantra sakti yang nyaris religius. Pejabat publik menyebutnya dengan khidmat, seperti sedang berderma dari kantong pribadinya. Guru mendapat bantuan tunjangan profesi. Siswa miskin diberi bantuan beasiswa. Sekolah rusak mendapat bantuan rehabilitasi. Bahkan saat pandemi, negara memberi bantuan kuota internet—seolah-olah sinyal itu datang dari surga melalui tangan kementerian. Dan akhir-akhir ini program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja (BOSP Kinerja) digelontarkan kepada sekolah-sekolah tertentu, yang sesungguhnya program ini telah ada sejak tahun 2019. Kata “bantuan” begitu deras mengalir dari podium ke media, dari ruang konferensi ke siaran pers, dari mulut pejabat ke kepala rakyat. Padahal jika kita mau menepi sejenak dari arus deras narasi ini, kita akan melihat absurditas yang menyakitkan: yang disebut “bantuan” itu bukan kemurahan hati, negara bukan sedang berbagi, tapi sedang membayar utang moralnya kepada rakyat.
Dalam logika bahasa yang sehat, “bantuan” mengandaikan adanya hierarki moral: pihak pemberi adalah sosok dermawan, sementara pihak penerima adalah makhluk kasihan yang sepatutnya berterima kasih. Namun, dalam konteks pendidikan formal yang dijamin undang-undang, relasi semacam ini adalah pengkhianatan terhadap makna negara itu sendiri. Pendidikan bukanlah hadiah, apalagi sedekah. Pendidikan adalah hak dasar. Ia tidak datang dari kemurahan hati siapa pun, melainkan dari kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pendidikan. Maka ketika pemerintah menyebut dana BOS sebagai “bantuan”, ketika siswa penerima KIP disebut “beruntung mendapat bantuan”, atau ketika guru honorer diberi upah dengan embel-embel “bantuan insentif”, yang sedang terjadi bukanlah distribusi keadilan, melainkan manipulasi bahasa atas nama kewajiban yang dikebiri.
Konstitusi kita jelas dan terang-benderang. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Ayat (4) bahkan secara eksplisit menetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, pendidikan adalah mandat negara, bukan kemurahan pejabat. Ketika pemerintah menyulap kata “pembiayaan wajib” menjadi “bantuan”, maka yang sedang terjadi adalah pemangkasan makna konstitusional atas nama citra. Negara tampil sebagai pahlawan pemberi hadiah, bukan sebagai pelaksana amanat rakyat.
Lebih tragis lagi, logika “bantuan” ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah bagian dari tata kelola neoliberal, di mana tanggung jawab negara dipreteli, lalu dikemas dalam logika pasar dan amal. Negara tidak lagi tampil sebagai penjamin hak, tetapi sebagai sponsor proyek sosial. Guru bukan lagi tenaga intelektual yang dijamin kesejahteraannya, tetapi sekadar penerima subsidi. Murid bukan lagi subjek belajar yang bermartabat, tetapi anak malang yang “dibantu” demi statistik. Bahasa seperti ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga merusak struktur kesadaran kita tentang keadilan.
Padahal, dari sisi anggaran, tidak ada yang perlu dibanggakan sebagai “bantuan”. Pada tahun 2024, berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai Rp665 triliun, setara dengan 20% dari total belanja negara. Uang ini bukan berasal dari dompet pribadi menteri atau belas kasih partai politik, melainkan dari pajak yang diperas dari keringat rakyat. Dana publik ini kemudian dikemas dalam berbagai label “bantuan”: BOS Reguler sebesar Rp54,65 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa afirmasi lebih dari Rp10 triliun, bantuan subsidi upah guru honorer sekitar Rp3,6 triliun pada tahun 2021, dan belasan triliun lainnya untuk program rehabilitasi sekolah. Pertanyaannya: jika uang rakyat dikembalikan untuk rakyat, mengapa masih disebut bantuan? Di titik ini, mungkin perlu kita balik logikanya—justru rakyatlah yang selama ini “membantu” negara agar tetap punya legitimasi.
Bahasa “bantuan” ini juga menciptakan efek psikologis yang cukup mengerikan: mengerdilkan rasa berhak. Guru-guru yang semestinya berdiri tegak menuntut profesionalisme, kini diam karena merasa “sudah dibantu”. Murid-murid yang seharusnya merasa berhak atas pendidikan, malah diajari untuk merasa beruntung jika dapat kuota internet atau bantuan seragam. Sekolah-sekolah yang semestinya mengelola anggaran dengan percaya diri sebagai penerima hak, justru ketakutan karena merasa hanya “dapat bantuan” yang bisa dicabut kapan saja. Inilah bentuk domestikasi sosial yang sangat halus namun efektif: rakyat diajari untuk bersyukur atas sesuatu yang sebetulnya adalah miliknya sendiri.
Kita tentu tidak anti terhadap kata “bantuan” dalam konteks kemanusiaan atau bencana alam. Tapi ketika kata yang sama digunakan dalam konteks pendidikan formal yang dijamin oleh konstitusi, maka kita sedang menyaksikan upaya sistemik untuk mengaburkan batas antara kewajiban dan kemurahan. Retorika ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus dibongkar, dilawan, dan dikoreksi.
Posisikan dengan benar makna asli dari kata hak, kewajiban negara, dan anggaran publik. Pemerintah bukanlah dermawan. Negara tidak sedang beramal. Guru bukan penerima belas kasih. Siswa bukan pengemis pengetahuan. Pendidikan bukan hadiah, melainkan fondasi kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. Jika masih ingin menyebut “bantuan”, mungkin perlu kita tanyakan ulang: bantuan dari siapa kepada siapa? Bukankah negara justru hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat?

Penulis adalah pemerhati pendidikan dan peneliti di Oase Institute
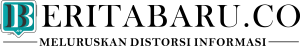

 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co