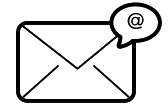Cermin untuk Dunia Pesantren | Opini: Zainul Abidin*
Kabar robohnya musolla di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, membuat kita berduka. Karena, peristiwa yang terjadi begitu dekat dengan kehidupan banyak pesantren di Indonesia. Sebagai orang yang juga tumbuh di dunia pesantren, saya tidak ingin melihat kasus ini sekadar sebagai musibah atau bahan saling tuding. Saya justru melihatnya sebagai cermin kecil dari cara hidup yang sudah lama jadi bagian dari tradisi kita.
Di banyak pesantren, santri sering ikut membantu pembangunan pondok — dari ngecat, menata batu bata, sampai ikut ngecor. Bukan karena dipaksa, tapi karena menilai bahwa ini bagian dari pengabdian, atau dalam bahasa santri: khidmah. Membantu kiai adalah kehormatan, bukan beban. Saya tahu persis, banyak pesantren dibangun dengan keringat dan keikhlasan. Banyak kiai yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengajar dan membimbing santri tanpa pamrih.
Jadi, berhentilah saling menyalahkan, ayo kita memaknai kembali pengabdian di zaman yang terus berubah.
Saya percaya, niatnya selalu baik. Tapi kadang, niat baik saja tidak cukup. Di balik semangat gotong royong itu, ada hal-hal yang perlu kita pikirkan ulang: soal keselamatan, soal tanggung jawab, soal bagaimana memastikan kerja bersama tetap aman bagi semua. Karena seikhlas apa pun niatnya, kalau berujung bahaya, itu tetap jadi tanggung jawab kita bersama.
Antonio Gramsci, seorang pemikir Italia, menyebut ada bentuk kekuasaan yang berjalan tanpa paksaan, yaitu hegemoni kultural—ketika nilai-nilai diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan. Di banyak pesantren, ketaatan pada kiai sering bekerja dengan cara seperti itu. Santri tidak merasa diperintah; mereka rela karena meyakini membantu kiai adalah ibadah. Hegemoni seperti ini tidak selalu buruk—ia menciptakan solidaritas dan disiplin moral.
Antropolog Clifford Geertz menggambarkan pesantren sebagai ruang patron–client yang khas: kiai sebagai patron spiritual, santri sebagai client religius. Relasi ini hangat dan penuh kasih sayang, tetapi tidak selalu setara. Di masa lalu, patronase ini berjalan alami. Kini, dalam dunia yang menuntut standar keselamatan dan profesionalitas, bentuk relasi itu perlu dimaknai ulang. Kiai tetap menjadi pusat moral, tetapi lembaga pesantren juga perlu memastikan bahwa pengasuhan spiritual disertai perlindungan sosial.
Apa yang terjadi di PP Al Khoziny bisa jadi pengingat bagi dunia pesantren, bahwa nilai-nilai lama tetap bisa hidup berdampingan dengan kesadaran baru. Kita tetap bisa menjaga semangat khidmah, tapi dengan cara yang lebih teratur dan aman. Kita tetap bisa menghormati kiai, tanpa meniadakan ruang dialog dan akal sehat. Kita tetap bisa menjaga keikhlasan, sambil tetap memastikan keselamatan.
Tragedi itu juga menunjukkan bahwa pesantren sedang berada di persimpangan penting: antara menjaga tradisi dan membangun tata kelola yang lebih modern. Dan saya yakin, pesantren bisa melakukannya — karena di balik semua keterbatasan, pesantren selalu punya satu hal yang paling kuat: ketulusan.
Mungkin inilah waktunya kita mengubah cara pandang: bahwa menjaga keselamatan santri juga bagian dari ibadah, bagian dari pengabdian, bagian dari cinta kepada ilmu dan guru. Karena barokah tidak datang dari pengorbanan yang menyakitkan, tapi dari niat baik yang diiringi tanggung jawab.
*Alumnus SMA Pesantren Al-In’am, Gapura, Sumenep
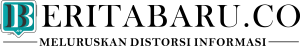
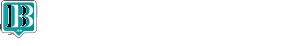
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co