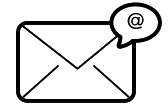Mengapa Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas | Opini: Musyarrafah S.
Seandainya gaji guru di Indonesia benar-benar tinggi dan layak, mungkin saya sendiri bukanlah orang yang terpilih menjadi guru.
Di titik itu ada satu hal yang sering dibalik logikanya: guru dianggap pantas digaji rendah karena kualitasnya dinilai rendah. Narasi ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya, sebab menutup kemungkinan adanya perbaikan struktural. Bagaimana mungkin kita berharap mutu tinggi dari sosok yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya?
Urutannya harus jelas: sejahterakan dulu guru, lalu bicarakan mutu. Profesi yang amat penting ini harus ditempatkan di atas fondasi kesejahteraan yang layak, agar mereka dapat bekerja tanpa dihantui kekhawatiran finansial. Setelah itu, di bab berikutnya barulah kita menuntut kualitas: standar rekrutmen yang lebih ketat, pengembangan profesional berkelanjutan, hingga evaluasi berbasis kinerja. Dengan demikian, kesejahteraan dan mutu tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkuat. Gaji tinggi bukan hadiah, tetapi investasi. Dan investasi itu harus diiringi dengan mekanisme penjaminan mutu yang sungguh-sungguh.
Sosiolog Randall Collins (1979) melalui teori credentialism menekankan bahwa pendidikan, termasuk profesi guru, selalu terkait erat dengan legitimasi sosial-ekonomi. Gaji yang tinggi bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan penegasan ekspektasi publik atas mutu yang wajib dijaga. Jika seorang dokter digaji tinggi karena bertaruh pada nyawa pasien, maka guru semestinya digaji tinggi karena bertaruh pada masa depan bangsa. Masalahnya, di Indonesia gaji guru kerap dijadikan “perisai retoris” untuk membenarkan kualitas yang belum optimal. Di satu sisi guru diminta berkorban atas nama pengabdian, di sisi lain negara masih enggan memberi kompensasi yang sepadan dengan beban moral dan intelektualnya.
Situasi ini mengingatkan pada analisis James C. Scott (1990) dalam Domination and the Arts of Resistance. Ia menyebut adanya perbedaan antara “narasi publik” dan “transkrip tersembunyi.” Dalam narasi publik, guru dielu-elukan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa.” Tetapi di baliknya ada transkrip tersembunyi: kegelisahan, keletihan, dan keresahan tentang kesejahteraan yang terabaikan.
Mari kita bayangkan sebuah titik balik. Saat gaji guru benar-benar tinggi, tidak ada lagi ruang untuk menoleransi rendahnya mutu. Guru tidak cukup hanya “mengabdi,” tetapi harus menunjukkan kapasitas profesional: menciptakan pembelajaran bermakna, mendidik karakter, dan melahirkan warga negara yang kritis. Dalam perspektif human capital theory (Becker, 1993), gaji guru adalah bentuk investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia bangsa. Dengan kompensasi yang layak, standar rekrutmen akan meningkat: hanya mereka yang benar-benar kompeten secara akademis, kreatif secara pedagogis, dan berintegritas secara moral yang dapat dipercaya. Profesi guru pun tidak lagi menjadi “tempat pelarian” dari jalur karier lain, melainkan sebuah puncak prestasi intelektual dan etis.
Sejak awal, narasi pendidikan di Indonesia kerap terjebak dalam dikotomi antara pengabdian moral dan tuntutan material. Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa pendidikan adalah “usaha kebudayaan yang bermaksud memberi tuntunan bagi tumbuhnya jiwa dan raga anak.” Namun, gagasan luhur itu jarang ditindaklanjuti dengan kesadaran politik bahwa tuntunan semacam ini hanya mungkin jika gurunya sejahtera. Dari sini saya berpijak pada satu logika sederhana: ketika gaji guru rendah, perjuangan utama adalah membela kesejahteraan; ketika gaji guru tinggi, perjuangan berikutnya adalah menuntut mutu. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dialektika historis yang seharusnya terus bergerak maju.
Mungkin benar, jika gaji guru tinggi, saya sendiri bukan lagi bagian dari profesi itu. Tetapi bukankah itu justru lebih baik? Sebab berarti yang menjadi guru adalah mereka yang benar-benar terbaik. Anak-anak bangsa dididik oleh pendidik yang tidak hanya mencintai profesinya, tetapi juga diakui oleh negara dengan penghargaan setara dengan pengorbanannya. Pada titik itu, guru bukan sekadar “pahlawan tanpa tanda jasa,” melainkan “pilar peradaban yang berdaya dan bermutu.”
Saya tetap menaruh harapan pada hari itu, hari ketika profesi guru ditempatkan pada puncak penghormatan negara dan masyarakat. Sebab, jika guru sudah sejahtera, tidak ada lagi kompromi selain mutu.

Musyarrafah S. merupakan kontributor tetap opini beritabaru co, peneliti Oase Institute, dan pemerhati pendidikan
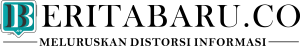
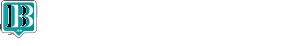
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co